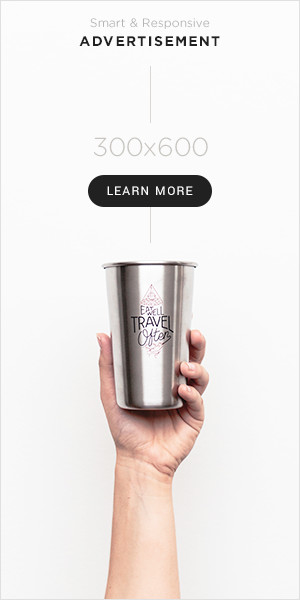SIAPA yang tak kenal Robert Nesta “Bob” Marley? Tapi mungkin tak banyak yang tahu kalau legenda musik reggae yang mashyur itu lahir dari rahim seorang budak kulit hitam. Segregasi kelas sosial yang sangat tajam dalam masyarakat Jamaika menjadikan si anak budak ini hidup dalam satu kata, ‘perjuangan’.
Ibunya yang budak itu bernama Cedella, sementara ayahnya Norval Sinclair Marley adalah seorang kulit putih. Namun, begitulah hidup. Ketika sekat pemisahan rasial telah menganak-pinak, hal-hal substansial dalam aspek manapun barang tentu mengalami keterlantaran tak terperi. Norval Marley yang angkuh dengan dandanan kulit putihnya pergi meninggalkan Cedella dalam kondisi hamil. Kita boleh saja menganggap Norval bedebah ataupun lelaki brengsek tak punya wibawa. Akan tetapi, Jamaika memang kala itu hidup dalam romantisme ekonomi dan politik yang serampangan. Jurang pemisah antara yang kaya dan miskin, yang putih dan yang hitam, yang kolonial dan yang budak sangat dalam terasa (bdk. Jube Tantagode, Reggae, Ayyana, 2012, hlm. 59-60).
Ibunya kemudian membawanya pindah ke Kingston, tepatnya di Trench Town. Di sinilah, Bob menemukan ‘panggilan’ hidupnya berlatarkan situasi jalanan yang penuh dengan minuman keras, konflik antargang, hingga kekerasan-kekerasan fisik lainnya. Menariknya, musik menjadikan anak-anak gang semacam dirinya terinspirasi untuk menentang kesemena-menaan penguasa. Irama R&B, Soul, dan Ska menjadi yang paling disukai sosok kelahiran Nine Miles, Jamaika, 06 Februari 1945. Tak pelak bahwa ragam musik itulah yang menggiringnya menguniversalkan genre fenomenal bernama ‘reggae’. Syahdan, Bob Marley pun mencoba menyanyikan lagu-lagu kesukaannya pada berbagai studio kecil di Kingston. Dari situlah, karirnya di dunia musik mulai terpatri. Ia berkenalan dengan para musisi dan penyanyi Jamaika lainnya. Hingga pada awal 1962, Bob Marley, Bunny Livingstone, Peter Tosh, Junior Braithwaite, Beverly Kelso dan Cherry Smith membentuk grup The Teenager yang kemudian berubah menjadi The Wailing Rudeboys, lalu The Wailing Wailer, hingga akhirnya The Wailers.

Tentu, ada begitu banyak cerita berkenaan dengan Bob Marley. Pengalaman-pengalaman, lika-liku perjuangan hidupnya memberikan kenangan bermakna bagi pencinta reggae khususnya, dan masyarakat dunia umumnya. Ini tentang bertahan dan mengembangkan hidup. Juga tentang bangun dari himpitan situasi yang tak kondusif, dan berjuang untuk tegar berdiri. Kisah Bob Marley memang tak pernah tuntas. Ada jutaan orang yang tetap setia mendengar (baca: mengabadikan) karya-karyanya. Lagu-lagu Bob Marley yang selalu lahir dari konteks sosial tertentu merupakan hiburan serentak peletup semangat untuk senantiasa berjuang dari keterpurukan. Selalu saja terdapat pesan yang hendak disampaikan “The Prophet”, begitulah ia disapa dalam kalangan rastafarian.
Sekali lagi, perjuangan hidup adalah kata kunci utama untuk mengeksplanasi keseluruhan perjalanan hidup sang legenda. Seperti yang sudah dikatakan, ia sudah merasakan itu sejak berada dalam kandungan ibu. Diskriminasi rasial yang berujung pada distorsi-distorsi sosial lainnya juga membuatnya berjuang untuk bisa “menemukan” diri. Namun, sekali lagi musik menginspirasinya. Bob Marley melihat musik (reggae) sebagai agama paling nyata baginya, terlepas dari anutan sebagai seorang rastafarian. Tatkala filosof Ludwig Feurbach mengatakan bahwa agama adalah produk manusia yang teralienasi, sebuah produk yang mana manusia kemudian kehilangan kontrol atasnya, dapat dikatakan bahwa musik bagi Bob Marley bukanlah pelarian dari rasa tertekan dan tertindas. Musik bagi pria putus sekolah ini adalah perjuangan itu sendiri, hal nyata yang bisa bermakna bagi banyak orang. Lagu-lagu awal semacam Judge Not, Terror, dan One Cup of Coffe (1962) merupakan refleksi atas bengisnya kolonialisme Inggris di Jamaika. Ataupun Simmer Down yang bercerita tentang rude boy, panggilan bagi anak-anak gang yang hidup dalam tawuran dan kekerasan. Adapun No Woman No Cry (1975) yang sakral itu berisikan hiburan dan penguatan kepada kaum wanita akibat kehilangan harga diri, keluarga, dan orang-orang yang dicintai sekitaran hidup mereka. Tak jarang, lagu-lagu Bob Marley pun mengusung ajakan revolusioner, semisal seruan perlawanan dalam Get Up, Stand Up dan berbagai lagu lain dalam album Burnin’ (1973).
Selain itu, Bob Marley lewat karya-karyanya turut menyerukan semangat perdamaian bagi rakyat Jamaika. Dengan ritual reggaenya, memejamkan mata sembari berjingkrak-jingkrak dan mengacungkan kepalan tangan, Bob menghipnotis semua penontonnya larut dalam setiap makna lagu-lagunya. Rasa cinta pada tanah airnya itu menghentaknya terlibat dalam konser The One Love Peace yang mana menghadirkan dua pemimpin politik yang bertikai kala itu, Michael Manley dan Edward Seaga. Aksi dramatis nan menyentuh pun disajikan. Bob Marley melantunkan lagu One Love diapiti kedua kubu yang berseteru, lalu mengangkat tangan Manley dan Seaga, dan menyatukan dalam satu kepalan tangan pertanda berakhirnya persengketaan kedua belah pihak (bdk. Jube Tantagode, ibid. hlm. 77). Sungguh luar biasa momen tersebut. Lagu One Love itu sendiripun menjadi semacam himne kemanusiaan internasional yang melampai sekat suku, agama, dan ras.
Hal lain yang ingin disuarakan “Sang Nabi” ialah soal cinta terhadap integritas diri. Pada prinsipnya, semua manusia itu sama, setara, dan sederajat. Oleh sebab itu, manusia bukanlah budak yang bisa diperalat begitu saja. Lagu Redemption Song (1980) menjadi salah satu daya kobar yang paling khas dengan jargonnya, “emancipate yourselves from mental slavery, none but ourselves can free our mind”. Artinya, Bob Marley sangat mendukung gerakan kaum kulit hitam, tidak hanya di Jamaika tetapi juga di Afrika, untuk bisa lepas dari setrapan rasialisme dan imperialisme. Bob Marley sadar bahwa dirinya merupakan anak seorang budak yang seringkali diperlakukan secara tidak adil. Makanya, dia ingin mengangkat harkat dan martabat kaumnya. Inspirasi dari ajaran Rastafari, sebuah kepercayaan yang melihat Kaisar Ethiopia Haile Selassie sebagai titisan Tuhan dengan teologinya bahwa Tuhan mahamengetahui dan mahamencintai, sangat memengaruhi diri Bob Marley. Sehingga tidaklah mengherankan kalau lagu-lagu Bob Marley seringkali diujarkan sebagai sabda-sabda Rastafarian.
Demikianlah beberapa poin seputar Bob Marley dan perjuangan kemanusiaannya. Bob Marley boleh jadi merupakan seorang nabi. Namun, hidupnya tak abadi. Ia wafat pada 11 Mei 1981. Kepergiannya menimbulkan duka mendalam bagi kaum Rastafarian dan para pencinta reggae umumnya. Akan tetapi, karya-karyanya selalu terngiang kekal dalam keseharian hidup penggemarnya. Kisah-kisah perjuangan dan keberpihakannya kepada kaum pinggiran semestinya menjadi motivasi bagi kita sekalian. Keberanian menyuarakan kaum tak bersuara lewat musik adalah ekspresi positif yang pantas diapresiasi. Memang harus diakui juga bahwa hidupnya tak mulus-mulus amat. Kisah perkelahian, kekerasan, kecanduan terhadap ganja adalah semacam warna lain dari sisi kelam hidupnya. Namun, filosofi perjuangan pada tataran yang lebih ekstensif adalah harga yang tak dapat dibayar. Sehingga miris saja apabila orang yang seringkali mendaku pencinta reggae hanya tahu bagaimana berjingkrak sana-sini dengan gaya rambut dreadlock, ataupun berkoar sana-sini tanpa punya kepedulian sosial terhadap realitas hidup.
Sekali lagi, kisah tentang Bob Marley takkan tuntas, dan sejatinya itu harus menjadi kisah perjuangan kita selanjutnya. Tentu itu dengan cara kita masing-masing. Dan, bisa jadi perjuangan kemanusiaan kita adalah kebanggaan lain bagi sang legenda yang telah pergi, selain bangga mengenakan cincin Lion of Judah kepunyaan Kaisar Haile Selassie. Selamat ulang tahun Om Bob, 06 Februari 2016.***
Penulis adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere. Sekarang bergiat pada Komunitas KAHE (Sastra Nian Tanah), sebuah kelompok minat terhadap sastra bentukan beberapa orang muda di Maumere, Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur.
Dikutip dari: https://indoprogress.com/2016/02/bob-marley-perjuangan-dan-kisah-kita/